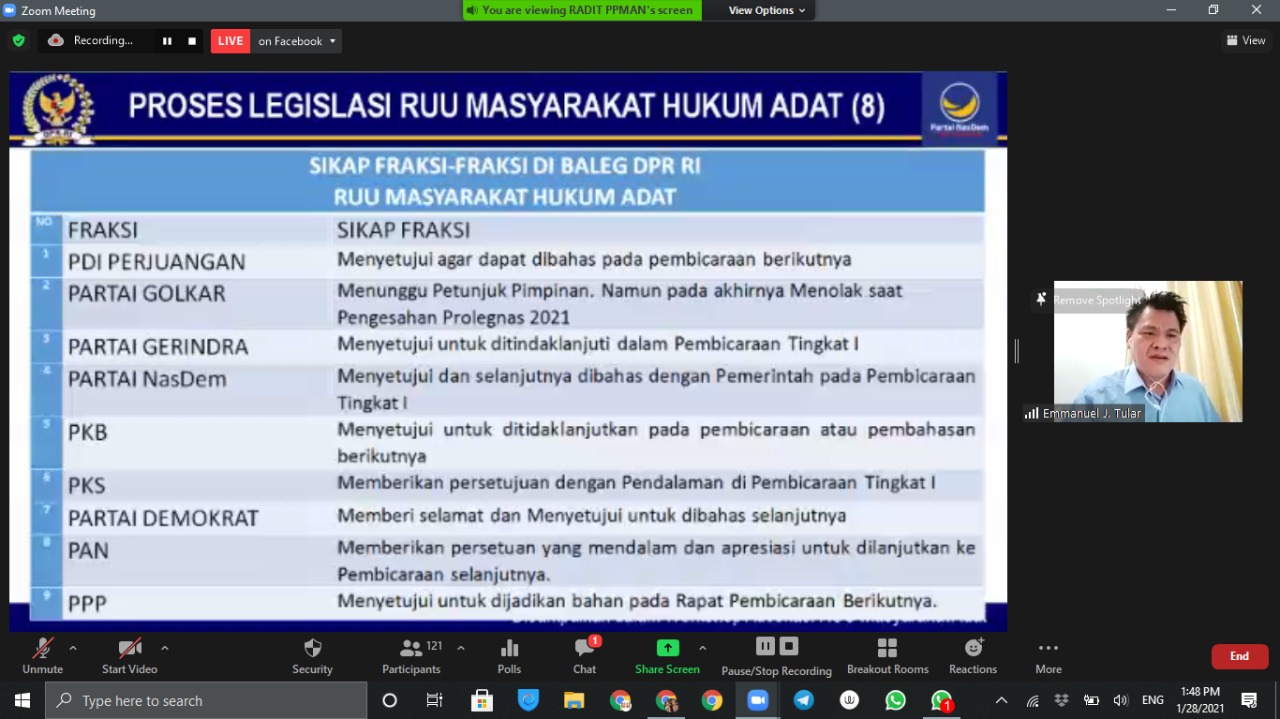
Substansi RUU Masyarakat Adat versi DPR Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Adat.
29 Januari 2021 BeritaRancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang-Undang. Peringatan itu dikemukakan Erasmus Cahyadi, Deputi II Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam dialog publik virtual bertema Menakar Tantangan & Peluang Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tahun 2021 yang digelar Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (28/1/2021) sore. Menurut Erasmus, sejumlah pasal yang ada pada draf RUU MA di DPR-RI sekarang, justru melenceng dari cita-cita awal lahirnya tuntutan RUU ini. “Kalau kita melihat rancangan sekarang di DPR, banyak sekali tema-tema yang justru berbahaya untuk agenda pengakuan Masyarakat Adat,” ucapnya. Ia mengatakan, saat ini, sebanyak 11 juta hektar wilayah adat se-Nusantara yang terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), 77% berada dalam kawasan hutan. Dan di sana terdapat banyak tumpang-tindih dengan perizinan dan peruntukan lain atas kawasan hutan itu. Menurutnya, hanya sedikit wilayah adat yang tidak berkonflik, kurang dari 10%. Tetapi, kata dia, dalam draf RUU MA di DPR-RI tidak memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian konflik itu. Ia mempertanyakan, bagaimana mengurus 77 persen wilayah adat yang ada di dalam kawasan hutan itu. “Apakah hanya bertumpu kepada Pasal 67 ayat 2 UU Kehutanan yang akan dilepaskan menjadi hutan adat? Sementara kita tahu persis bahwa hutan adat yang dilepaskan itu bukanlah wilayah adat,” ujar Erasmus. Menurutnya, hutan adat yang ada saat ini hanya menjadi bagian kecil dari total wilayah adat. “Saya ambil contoh wilayah adat Kajang, hampir itu 23 ribu hektar. Tapi yang sekarang hanya mendapatkan legalitas berdasarkan hutan adat itu paling tidak hanya 300 hektar. Pertanyaannya 22 ribu sekian hektar itu, status legalnya apa? Ini harusnya dijawab oleh RUU Masyarakat Adat ini!” Ia berpendapat UU Masyarakat Adat kelak harus membuka diri terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang telah terjadi. Ini agar konflik-konflik itu tidak berulang erus menerus. “Artinya diputus, dan kemudian diketemukan bagaimana menyelesaikan. Itulah yang kita sebut dalam rancangan lama yang kita usulkan itu dalam satu bab restitusi dan rehabilitasi.” Erasmus juga menyoroti pentingnya menghilangkan rancangan bab tentang evaluasi keberadaan Masyarakat Adat dalam RUU itu. Kenapa ini harus dihilangkan? Karena bab ini bisa dijadikan alat mendelegitimasi keberadaan Masyarakat Adat. “Karena hukum itu dikerjakan birokrat yang di belakang kepalanya punya pandangan tertentu tentang politik ekonomi dll. Sepanjang sejarah kita terlalu khawatir ketika negara diberikan kekuasaan yang berlebihan untuk hal-hal yang semcam ini. Itu bisa dijadikan alat mendelegitimasi keberadaan Masyarakat Adat,” bebernya. Kemudian ia menilai rancangan yang menyebut penetapan Masyarakat Adat di tangan Menteri Dalam Negeri harus diubah. “Sekarang ini saja, proses pengakuan itu ada dua jalur. Ada melalui peraturan daerah, ada melalui keputusan kepala daerah. Dua-duanya juga tidak mudah bagi Masyarakat Adat.” Ia juga mempersoalkan hilangnya usulan pembentukan Komisi Masyarakat Adat dalam RUU. Menurutnya komisi ini penting karena masalah sektoralisme dalam pengakuan Masyarakat Adat selama ini. “Maka mesti ada suatu kelembagaan negara yang mengkoordinasikan seluruh program pengakuan, pemberdayaan dan pemajuan Masyarakat Adat. Itulah yang kita sebut dengan Komisi Masyarakat Adat itu,” jabarnya. Yang tak kalah penting menjadi sorotan, RUU yang ada sekarang masih minim pengaturan untuk merespon situasi berbeda dalam Masyarakat Adat. Ini misalnya, terkait dengan hak-hak perempuan. “Itu juga harus direspon untuk dimasukkan secara komprehensif dalam rancangan yang sekarang ada.” Lalu, soal proses pendaftaran Masyarakat Adat untuk memperoleh pengakuan. Menurut Erasmus, harusnya ada dua metode yang diberikan. Pertama, melalui pemerintah, yang diatur dalam RUU ini. Kedua, kata dia, harusnya juga bisa melalui putusan pengadilan. Caranya, dengan meletakkan kewenangan di pengadilan untuk memberikan penetapan terhadap subjek hukum Masyarakat Adat. “Jadi prosesnya sama. Masyarakat Adat itu akan membawa berkas-berkas usulan penetapannya ke pengadilan. Pengadilan yang akan memverifikasi dll.” Terakhir Erasmus menyinggung keberadaan UU Cipta Kerja (CILAKA) dan UU Mineral dan Batubara yang baru disahkan 2020. Kedua UU ini dinilai dapat mengancam keberadaan Masyarakat Adat. “Yang menarik adalah, tantangan besar, bagaimana posisi UU Masyarakat Adat dengan UU Minerba dan Cipta Kerja. Apakah lex specialist atau apa?” Terkait dengan masalah penanganan konflik dan ketiadaan Komisi Masyarakat Adat, pakar hukum dari Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Rikardo Simarmata punya pertanyaan. Apakah ketiadaan pengaturan soal penanganan konflik yang sudah terjadi terkait dengan tak adanya rancangan aturan soal Komisi Masyarakat Adat? “Apakah sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau kita kaitkan dengan tiadanya ketentuan kelembagaan soal Komisi Nasional—yang bayangan kita diberikan kewenangan mengkoordinasi urusan Masyarakat Adat—apakah itu ada kaitannya dengan tidak dilihatnya tumpang-tindih itu sebagai alasan untuk membuat UU ini. Kalau itu tidak dijadikan alasan itu memang tidak perlu direspon dengan cara membuat mengatur mengenai kelembagaannya,” kata dia. Rikardo lantas menyoroti, banyaknya poin-poin substansial yang tak diakomodasi sebagai suasana kebatinan yang gundah dari penyusun RUU Masyarakat Adat. “Antara melihat masyarakat hukum adat sebagai komunitas rentan dan marginal dan karena itu perlu dilindungi negara, atau sikap khawatir terhadap kehadiran Masyarakat Adat kalau ditetapkan. Itu bisa kita lihat dari pengakuan, evaluasi, kewajiban yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.” **Budi Baskoro





